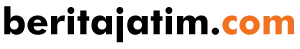Perkiraan Waktu Baca: 4 menit
Tentang Rumput yang Mendengarkan dan Laba yang Tak Terlihat

Seorang investor pragmatis bertemu dengan seorang visioner eksentrik yang mengklaim alun-alun kota adalah aset paling berharga, bukan karena tanahnya, tapi karena rumputnya yang memiliki kemampuan ajaib. Percakapan mereka membuka tabir sebuah model bisnis yang berada di antara jenius dan gila, menantang definisi kata "menguntungkan" itu sendiri.
Pertanyaan yang Salah dan Secangkir Kopi Pahit
"Jadi, Pak Sobirin," kata Bu Laras sambil mengetuk-ngetuk pulpennya di atas buku catatan bersampul kulit. "Bisa kita langsung ke intinya? Saya sudah lihat proposal Anda. Investasi di Alun-Alun Kota Ambarawa. Secara konsep, menarik. Lokasi premium. Tapi saya tidak melihat proyeksi ROI, analisis EBITDA, atau bahkan rencana monetisasi yang jelas. Yang ada hanya tiga halaman puitis tentang 'jiwa sebuah kota'."
Pak Sobirin, seorang pria dengan kemeja batik yang warnanya sudah menyerah pada takdir dan sepasang sandal jepit yang tampak lebih bijaksana darinya, menyesap kopinya dengan tenang. Mereka duduk di sebuah warung sederhana di tepi alun-alun. Angin sore membawa aroma samar bakso dan kebahagiaan anak-anak yang bermain layangan.
"Bu Laras," jawab Sobirin setelah jeda yang cukup lama untuk membuat seorang eksekutif mempertanyakan pilihan hidupnya. "Anda menanyakan pertanyaan yang salah. Itu seperti bertanya pada seorang penyair, berapa laba per bait dari puisinya. Anda tidak mengukur alun-alun dengan metrik kantor. Anda mengukurnya dengan..." ia berhenti sejenak, mencari kata yang pas, "...getaran."
Bu Laras menghela napas. "Pak Sobirin, saya tidak menginvestasikan dana pensiun nasabah saya berdasarkan 'getaran'. Saya butuh angka. Data. Sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam spreadsheet."
"Tentu saja ada data," kata Sobirin, senyumnya melebar. "Datanya ada di sana." Ia menunjuk dengan dagunya ke hamparan rumput hijau yang luas di tengah alun-alun. "Di setiap helai rumput itu."
Aset Bernama Rumput Memoria Sintetis
Bu Laras mengikuti arah pandang Sobirin. Ia hanya melihat rumput. Hijau, terawat baik, dengan beberapa area yang sedikit botak karena terlalu sering dijadikan gawang dadakan. "Maksud Anda rumput Jepang? Atau rumput gajah mini? Apa kita akan masuk ke bisnis agrikultur?"
"Bukan, Bu. Ini bukan rumput biasa," bisik Sobirin, mencondongkan tubuhnya seolah akan membocorkan rahasia negara. "Ini adalah varietas yang saya kembangkan sendiri selama lima belas tahun. Saya menyebutnya Rumput Memoria Sintetis."
Bu Laras menatapnya kosong. "Rumput... Memori... Sintetis?"
"Tepat," kata Sobirin, matanya berbinar. "Setiap helai rumput ini memiliki struktur seluler klorofil yang dimodifikasi secara biologis untuk berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan data pasif. Bukan data digital, Bu. Jauh lebih berharga dari itu. Rumput ini menyerap dan merekam jejak emosional."
Keheningan yang canggung menyelimuti meja mereka, hanya dipecah oleh suara penjual es doger yang lewat.
"Jejak... emosional?" ulang Bu Laras, pelan. Ia mulai curiga kopi yang disajikan di warung ini mengandung zat adiktif non-standar.
"Betul sekali!" seru Sobirin, terlalu antusias. "Tawa pertama seorang balita saat digelitik ayahnya, terekam. Kegugupan seorang remaja pada kencan pertamanya di bangku itu, terekam. Kekecewaan kolektif saat tim sepak bola lokal kalah di final, terekam. Kegembiraan saat ada festival dangdut gratis minggu lalu... wah, itu datanya pekat sekali, Bu. Butuh tiga hari sampai rumputnya kembali tenang."
Ia melanjutkan, "Alun-alun ini bukan sekadar tanah kosong. Ini adalah hard drive biologis raksasa yang mencatat denyut nadi emosional seluruh kota. Dan data ini, Bu Laras, adalah komoditas paling murni dan paling langka di dunia."
Demonstrasi Produk dan Gendang yang Samar
Bu Laras memijat pelipisnya. "Baik. Anggap saja... anggap saja saya percaya satu persen dari omong kosong ini. Bagaimana Anda 'memonetisasi' kebahagiaan kolektif dan kekecewaan penggemar dangdut?"
"Ah, bagian terbaiknya!" Pak Sobirin berdiri dan memberi isyarat agar Bu Laras mengikutinya. "Demonstrasi produk."
Dengan ragu, Bu Laras mengikuti Sobirin ke tengah alun-alun. Pria itu menggelar sebuah tikar pandan sederhana di atas hamparan rumput yang paling hijau. "Silakan, Bu. Berbaringlah."
"Saya tidak akan berbaring di sini, Pak."
"Hanya lima menit. Anggap saja ini bagian dari due diligence," bujuk Sobirin dengan senyum paling meyakinkan yang bisa ia kerahkan.
Setelah perdebatan internal yang sengit antara sisi profesional dan sisi penasarannya yang kini sudah tak terbendung, Bu Laras akhirnya menyerah. Dengan canggung, ia melepaskan sepatunya dan berbaring di atas tikar, merasa konyol luar biasa.
"Sekarang, pejamkan mata dan rileks. Jangan mencoba merasakan apa pun. Biarkan rumput yang bekerja," instruksi Sobirin.
Bu Laras memejamkan mata, siap untuk tidak merasakan apa-apa selain rasa malu. Detik pertama, hening. Detik kedua, hanya suara angin. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Ia merasakan gelombang kehangatan yang samar, seperti kenangan akan selimut di masa kecil. Lalu, muncul perasaan gembira yang meluap-luap tanpa sebab, begitu murni, seperti saat ia berhasil menaiki sepeda untuk pertama kali. Kemudian, sekelumit rasa rindu yang melankolis, disusul oleh sensasi dingin es serut di tenggorokan pada hari yang panas.
Dan yang paling aneh... di kejauhan kesadarannya, ia seperti mendengar alunan kendang dan suling yang sangat samar, membawakan irama dangdut yang familier. Itu nyata, tapi juga tidak.
Lima menit kemudian, saat Sobirin menepuk bahunya, Bu Laras membuka mata dengan ekspresi wajah yang campur aduk antara kaget, bingung, dan... damai.
Valuasi Berdasarkan Kebahagiaan Kolektif
"Bagaimana?" tanya Sobirin.
Bu Laras duduk perlahan. "Saya... saya mendengar dangdut."
"Ah, sisa-sisa festival minggu lalu. Efeknya masih kuat," kata Sobirin sambil mengangguk puas. "Anda juga merasakan kebahagiaan anak kecil yang baru dapat layangan baru, kan? Dan nostalgia seorang pensiunan yang mengenang istrinya? Itu data dari hari Selasa sore."
Bu Laras terdiam. Logikanya hancur berkeping-keping. Spreadsheet dan proyeksi ROI terasa seperti konsep dari peradaban lain.
"Jadi, ini model bisnisnya," jelas Sobirin, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. "Kita tidak menjual rumputnya. Kita menyewakan 'pengalaman'. Orang-orang datang ke sini, membayar biaya langganan bulanan yang terjangkau, untuk berbaring selama tiga puluh menit dan menyerap emosi positif yang telah dikurasi. Stres kerja? Datang ke sini, serap kebahagiaan murni dari anak-anak. Merasa kesepian? Datang ke sini, rasakan kehangatan cinta pertama yang terekam di dekat bangku taman. Ini adalah spa mental paling organik di dunia."
Ia menatap mata Bu Laras. "Investasi ini bukan tentang properti, Bu. Ini tentang kesejahteraan. Profitnya tidak diukur dengan Rupiah, tapi dengan 'Unit Kebahagiaan Standar' yang kita catat. Dan percayalah, Bu, dalam ekonomi masa depan, kebahagiaan adalah mata uang yang paling stabil."
Bu Laras memandang kembali ke hamparan rumput itu, yang kini tidak lagi terlihat biasa. Ia melihatnya sebagai ladang data emosional yang tak ternilai. Ia lalu menatap Pak Sobirin, si visioner gila bersandal jepit. Mungkin, pikirnya, inilah bentuk investasi paling menguntungkan yang pernah ada. Ia hanya perlu membuat metrik baru di spreadsheet-nya: "Laba per Senyuman."
Illustration: "A pragmatic businesswoman in a sharp business suit lies stiffly on a vibrant green lawn in a town square. Her eyes are wide with confusion. Around her, faint, ghostly images of everyday life are subtly visible in the air: a child chasing a kite, an old couple holding hands, a spectral ice-cream cart. An eccentric, relaxed man in a simple shirt and sandals sits cross-legged nearby, sipping coffee and looking at her with a knowing, serene smile. The entire scene has a surreal, dreamlike quality."